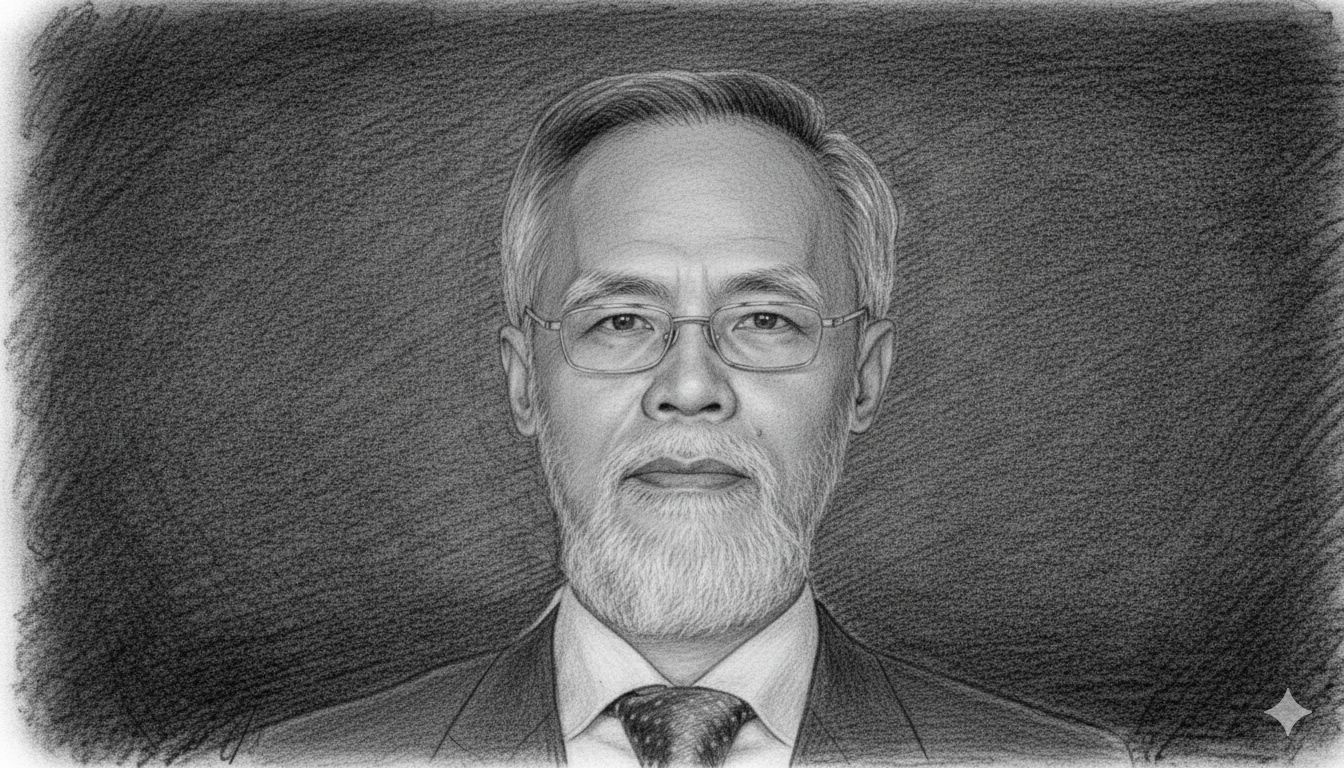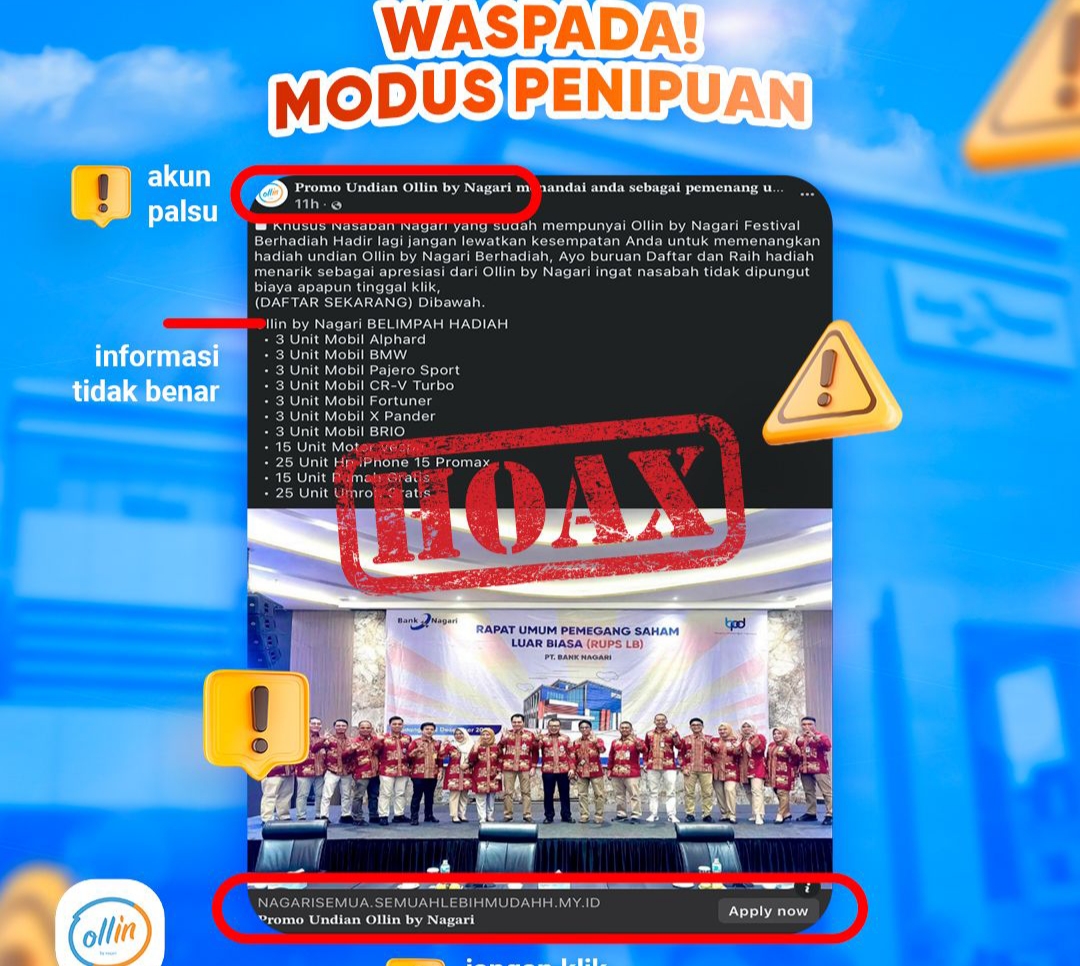Bencana alam selalu datang sebagai ujian paling jujur bagi sebuah kepemimpinan. Ia tidak dapat direkayasa, tidak bisa dipoles, dan tidak tunduk pada pencitraan. Di hadapan bencana, rakyat tidak menuntut retorika yang indah, melainkan kehadiran negara yang tulus, cepat, dan rendah hati. Namun dalam banyak peristiwa, yang justru muncul adalah narasi defensif negatif dari para pemimpin negara—narasi yang berujung pada pembenaran diri, saling klaim jasa, hingga permintaan maaf yang hampa makna substantif.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia berulang, lintas rezim, lintas konteks, dan lintas negara. Polanya hampir seragam: ketika kritik publik menguat, ketika solidaritas masyarakat bergerak lebih cepat dari negara, atau ketika bantuan internasional datang lebih dahulu, sebagian pemimpin justru sibuk melindungi citra, bukan memusatkan energi pada pemulihan korban. Dalam situasi genting, kepemimpinan berubah menjadi arena pertahanan ego.
Defensif Negatif sebagai Gejala Kepemimpinan Rapuh
Narasi defensif negatif biasanya muncul dalam kalimat-kalimat yang tampak sederhana namun sarat makna kuasa: “Negara masih mampu,” “Kita tidak butuh bantuan luar,” atau “Pemerintah sudah bekerja.” Secara formal, pernyataan ini terdengar wajar. Namun dalam konteks penderitaan korban bencana, ia sering berubah menjadi simbol penolakan terhadap empati dan partisipasi kolektif yang lebih luas.
Ketika bantuan luar negeri ditampik dengan alasan harga diri nasional, yang sebenarnya sedang dipertaruhkan bukan kedaulatan, melainkan ego politik. Negara seolah takut terlihat lemah, padahal dalam etika kemanusiaan, menerima bantuan adalah bentuk tanggung jawab moral, bukan tanda ketidakmampuan. Kedaulatan sejati justru diuji oleh kemampuan negara menempatkan keselamatan rakyat di atas simbol dan gengsi.
Meremehkan Solidaritas Dari Bantuan “Kecil” hingga Klaim Jasa
Fenomena lain yang kerap muncul adalah narasi yang meremehkan bantuan pihak lain. Bantuan luar negeri disebut “tidak seberapa”, bantuan masyarakat sipil dianggap pelengkap, sementara negara menampilkan diri sebagai aktor utama yang paling berjasa. Di sini, solidaritas berubah menjadi kompetisi simbolik, bukan kolaborasi kemanusiaan.
Ironisnya, dalam banyak kasus, justru masyarakat sipil, relawan, organisasi kemanusiaan, dan komunitas lokal yang hadir lebih dahulu di lokasi bencana. Ketika negara datang belakangan, alih-alih mengapresiasi, yang muncul adalah upaya mengambil alih narasi. Negara ingin tetap menjadi pusat cerita, bahkan ketika kerja-kerja kemanusiaan telah dilakukan oleh banyak tangan tanpa pamrih.
“Pemerintah Juga Bekerja”, Kalimat yang Menutup Dialog
Pernyataan bahwa “pemerintah juga bekerja” sering kali muncul sebagai respons terhadap kritik publik. Secara normatif, benar bahwa negara bekerja. Namun ketika kalimat ini digunakan untuk membungkam kritik, ia berubah menjadi alat defensif, bukan penjelasan akuntabel. Ia tidak lagi membuka dialog, melainkan menutup ruang evaluasi.
Dalam situasi bencana, masyarakat tidak sedang mempertanyakan niat bekerja, melainkan kecepatan, ketepatan, dan keberpihakan. Ketika kritik dijawab dengan pembelaan diri, kepercayaan publik justru semakin tergerus. Kepemimpinan yang kuat tidak alergi terhadap kritik, apalagi dalam konteks nyawa dan penderitaan manusia.
Pencitraan di Tengah Luka
Salah satu gambaran paling problematik dari kepemimpinan defensif adalah praktik pencitraan di lokasi bencana. Pemimpin datang dengan kamera, memanggul beras, mengenakan rompi khusus, lalu memastikan setiap gerak terekam dan tersebar luas. Secara simbolik, ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian. Namun secara etis, ia sering terasa seperti eksploitasi penderitaan.
Korban bencana membutuhkan sistem, bukan simbol. Mereka membutuhkan logistik yang berkelanjutan, hunian sementara yang layak, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Ketika kunjungan pemimpin lebih fokus pada visual daripada kebijakan, maka yang hadir bukan kepemimpinan, melainkan pertunjukan empati yang dangkal.
Pemimpin Negara seperti sedang Bersaing dengan Rakyatnya Sendiri
Dalam banyak peristiwa, muncul kesan bahwa pemimpin negara sedang “bersaing” dengan masyarakat. Ketika rakyat bergerak menggalang donasi, negara ingin terlihat lebih dominan. Ketika relawan bekerja senyap, negara ingin tampil paling berjasa. Ini adalah paradoks kepemimpinan: negara lupa bahwa masyarakat bukan lawan, melainkan mitra.
Bencana seharusnya menjadi momen penyatuan energi sosial. Negara berperan sebagai orkestrator, bukan solis tunggal. Ketika negara justru merasa terancam oleh solidaritas rakyat, itu menandakan krisis kepercayaan diri institusional. Kepemimpinan berubah dari melayani menjadi mempertahankan posisi simbolik.
Permintaan Maaf yang Terlambat dan Kosong Makna
Puncak dari narasi defensif negatif sering berujung pada permintaan maaf. Namun permintaan maaf ini kerap datang terlambat, setelah kritik membesar dan legitimasi tergerus. Lebih problematis lagi, permintaan maaf sering tidak diikuti perubahan kebijakan yang nyata.
Maaf yang tulus bukan sekadar ucapan, melainkan komitmen struktural untuk memperbaiki. Tanpa reformasi sistem penanganan bencana, tanpa evaluasi terbuka, dan tanpa pelibatan publik, permintaan maaf hanya menjadi penutup episode, bukan awal pembelajaran.
Menuju Kepemimpinan yang Berbasis Cinta dan Kerendahan Hati
Pemimpin negara perlu menyadari bahwa cinta kepada rakyat bukanlah slogan, melainkan praktik. Cinta dalam kepemimpinan terwujud dalam keberanian untuk mengakui keterbatasan, membuka diri terhadap bantuan, dan menempatkan korban sebagai pusat kebijakan, bukan sebagai latar pencitraan.
Kerendahan hati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Pemimpin yang berkata: “Kami membutuhkan bantuan demi keselamatan rakyat” sedang menunjukkan integritas moral yang tinggi. Ia tidak kehilangan wibawa tetapi justru memperolehnya melalui kejujuran.
Saran Normatif bagi Pemimpin Negara
Pertama, ubahlah paradigma dari defensif ke kolaboratif. Dalam bencana, negara harus menjadi penghubung seluruh energi kemanusiaan baik lokal maupun global tanpa rasa terancam. Kedua, pisahkan kerja kemanusiaan dari kepentingan pencitraan. Biarkan kebijakan berbicara lebih lantang daripada foto dan video.
Ketiga, bukalah ruang evaluasi publik yang jujur dan partisipatif. Kritik bukan musuh negara, melainkan cermin perbaikan. Keempat, tanamkan etika empati dalam setiap keputusan: tanyakan selalu, apakah kebijakan ini meringankan penderitaan korban atau sekadar melindungi citra kekuasaan.
Kepemimpinan yang Dikenang oleh Luka yang Disembuhkan
Sejarah tidak mengingat pemimpin dari seberapa sering ia tampil di kamera, tetapi dari seberapa banyak luka yang berhasil ia sembuhkan. Dalam bencana, rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang paling defensif, melainkan yang paling hadir secara bermakna.
Kepemimpinan sejati adalah keberanian untuk mencintai rakyat lebih dari mencintai citra diri. Dan dalam ujian bencana, hanya pemimpin seperti itulah yang akan dikenang. Pemimpin bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai manusia yang memanusiakan.
*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)