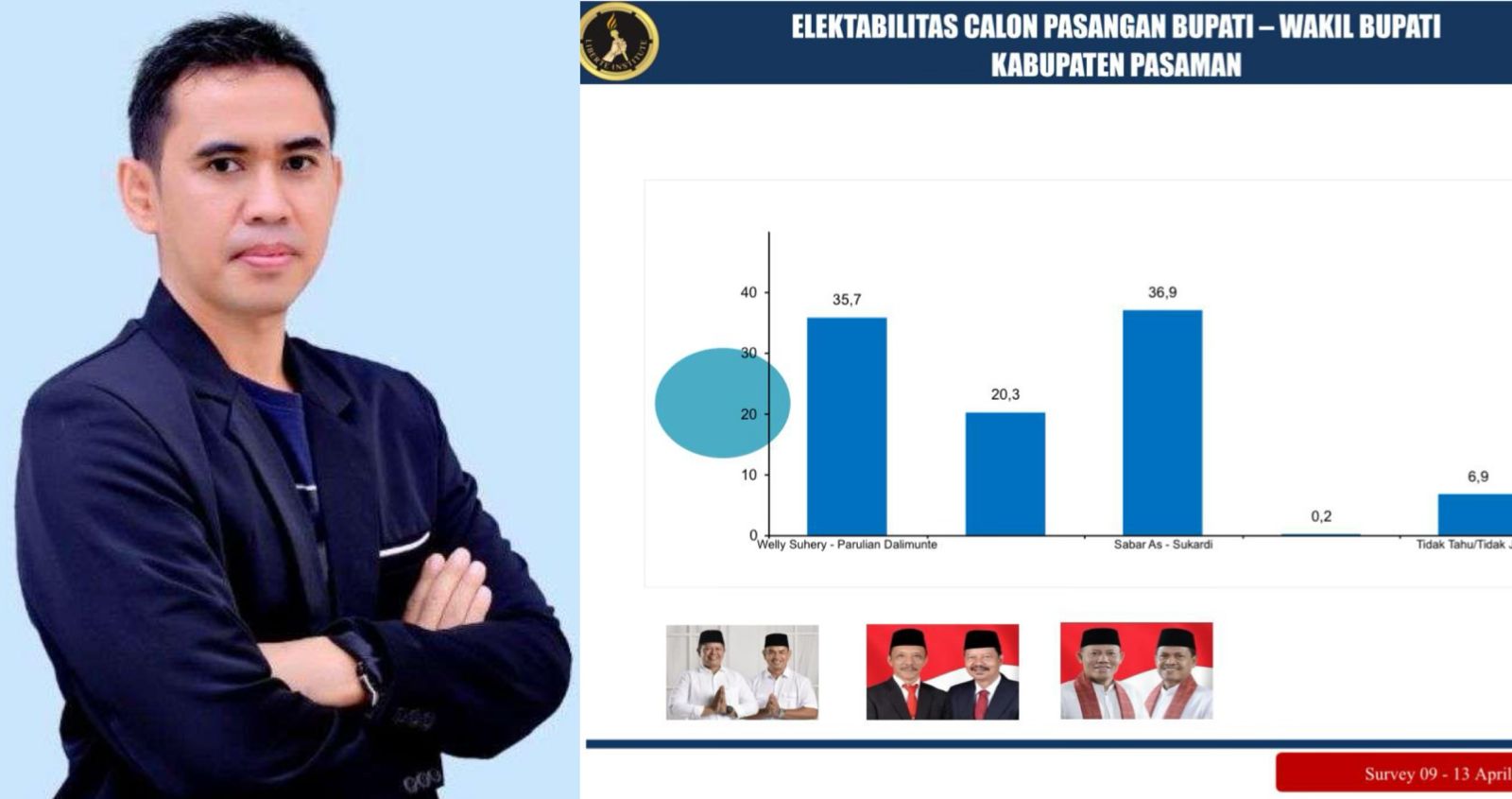Leksikon adalah kumpulan kata-kata yang ada di dalam kepala seseorang. Leksikon ini didapat dari pengalaman perorangan melalui interaksinya dengan alam dan segala yang ada di alam, baik berupa suatu yang nyata maupun sesuatu yang tidak nyata.
Biasanya leksikon-leksikon itu terhubung dalam kepala sesorang seperti bagaimana yang ada di alam. Kita tidak pernah melihat satu benda saja, pasti benda itu ada di sekeliling benda lain.
Hubungan-hubungan itu yang kemudian disebut konstruksi atau rangkaian. Hubungkait antara masing-masing elemen dalam rangkaian itu yang kita sebut pemaknaan. Lazim juga kalau hubungan-hubungan itu disebut dengan istilah bangunan atau struktur.
Dalam dunia nyata ada yang kita sebut dengan kursi, meja, lampu, jendela dan pintu. Hubungan semua elemen itu dapat kita sebut sebagai ruang tamu, ruang kelas atau apa saja. Oleh karena itu maka kita dapat mengatakan bahwa realitas yang dihubungkan di dalam kepala adalah struktur batin.
Kita perlu memahami bagaimana struktur batin itu terbentuk. Paradigma awal mengatakan bahwa struktur batin itu dibentuk oleh struktur alam yang konkrit yaitu alam. Indera manusialah yang menyusun ulang struktur lahir yang ada di alam itu masuk ke dalam struktur batin.
Jika bertemu dengan pical, lotek, ketoprak dan gado-gado, maka di dalam kepala kita akan terjadi penyusunan struktur untuk membedakan masing-masing realitas itu menjadi satu-satu leksikon yang berbeda.
Hal yang sama juga terjadi untuk konsep-konsep yang abstrak, meski elemen pembentuknya susah untuk dijelaskan, contoh seperti leksikon ‘cinta’, ‘sakik ati’ dan ‘sadiah.’ Dan jika rasa atau emosi tidak dapat diungkapkan dengan satu leksikon tersendiri, maka dibutuhkan metafora yang diambil dari leksikon yang sudah ada.
Hal yang perlu kita pahami dari perbincangan di atas adalah tentang peran bahasa sebagai alat untuk mengkonsepsi realitas. Dalam fase lebih awal, hal ini dapat juga dikatakan bahwa bahasa berfungsi sebagai representasi dari realitas. Untuk mewacanakan realitas dan membangun makna tersendiri, bahasa lah yang memiliki peran. Lalu kita mengenal apa yang disebut dengan teks atau disebut juga sebagai realitas yang terkonsepsi dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya.
Ternyata teks-teks tersebut dianggap sebagai sesuatu realitas baru. Dia ada dan dianggap benar. Saya adalah pengajar di sebuah perguruan tinggi adalah sebuah teks dan itu dapat dikatan sebagai realitas dan itu dapat dikatakan benar.
Jika seseorang mengetahui itu dan mengabarkan kepada orang lain, maka itu disebut sebagai fakta, dan fakta itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan jika dilihatkan foto atau videonya maka orang lain percaya bahwa itu adalah fakta dan itu adalah benar. Kebenaran ini yang kemudian disebut sebagai kebenaran pengalaman yang konseptual.
Kebenaran seperti ini disebut juga dengan kebenaran yang positivistik. Dunia modern dengan dorongan oleh filsuf-filsuf barat kemudian menjajakan kebenaran yang dianggap nyata seperti ini ke dunia lain yang mereka anggap sebagai tradisionalis atau ber-kebenaran lama. Dengan pendekatan seperti ini maka filsuf-filsuf ini kemudian menggantikan peran agama yang membawa kebenaran dogmatis. Mereka menjadi nabi baru. Jadi jika tuan-tuan menjadi tidak beragama, itu lah puncak dari modernitas itu. Ungkapan yang lazim di dunia baru adalah “agama tidak lagi relevan; sekarang sains lebih relevan; I don’t believe in god; I believe in science.”
Ruang dan waktu secara alamiah dapat menawarkan perubahan, termasuk perubahan konsepsi. Kita harus mengakui bahwa alat untuk mengakses pikiran dan membentuk konsepsi adalah bahasa. Aliran-aliran baru dalam filsafat bahasakemudian menggunakan bahasa ini untuk keinginan lain. Satu cabang ilmu yang dipengaruhi oleh filsafat bahasa adalah ilmu antropologi.
Jika kita melihat kisah lama (sejarah), sebelum masuk tentara ke negara jajahan, antropolog lebih dahulu masuk. Antropolog atau etnografer masuk ke kampung-kampung memahami bagaimana realitas dipahami oleh orang-orang kampung itu. Mereka mencari bagaimana orang-orang kampung itu memahami dunia dan bagaimana mereka memahami dirinya sendiri.
Setelah itu terpahami dengan baik, maka masuklah tentara sehingga akhirnya tanah dan apa-apa yang ada di dalam perutnya dapat dikuasai dengan efektif dan efisien. Itu terjadi di mana-mana dan umumnya yang melakukan itu adalah anak-kemenakan filsuf-filsuf tadi.
Perang dunia kedua kemudian mengakhiri babak ini, kira-kira. Para penjajah sesama mereka pun bertengkar-tengkar. Namun kita perlu mencatat sisi lain dari ini. Penjajahan di sisi lain dapat menjadi sumber kemajuan dari bangsa-bangsa yang disebut terbelakang. Mereka mengenal sekolah dengan sistem baru dan menggunakan bahasa penjajah. Lalu mereka meninggalkan bahasa kampung mereka atau bahasa lain yang dipakai untuk mengakses pikiran mereka. Mereka-mereka tamatan Kweekschool Fort de Kock adalah beberapa contohnya.
Selepas perang dunia dua usai, makin banyak saja antropolog masuk ke Sumatra ini. Tidak saja dari benua Eropah tetapi juga dari Amerika dan orang-orang lain yang saya tidak tahu pasti. Pokoknya banyak lah itu. Mereka masuk ke kampung-kampung dan menulisnya. Mereka merekam apa saja perangai orang-orang kita. Mereka masuk dengan senyuman dan dibantu oleh sarjana-sarjana lokal untuk kebutuhan yang disebut dengan penelitian akademik. Wah…sungguh sedap.
Sejak masa itu kita tertawan tidak lagi oleh tentara, tetapi oleh leksikon. Orang semakin banyak menulis dan membaca. Mereka meninggalkan leksikon-leksikon lama dan memakai leksikon-leksikon baru yang dibuat, dikategorikan, dan dimaknai oleh para peneliti itu. Setiap yang bisa menggunakan leksikon-leksikon baru itu dianggap lah sebagai orang terdidik, orang modern dan orang hebat. Satu sisi mereka orang lokal ini tidak sadar bahwa ‘pangana’ mereka sudah ditentukan oleh ilmu pengetahuan atau sains yang berangsur-angsur menggantikan kepercayaan mereka sebelumnya.
Pada awal enam puluhan ada satu bidang ilmu yang mulai berkembang cepat, yaitu psikologi kognitif. Bahasa sebagai alat utama untuk memindah-alihkan konsep ke dalam dan ke luar kepala menjadi salah satu kunci utama dalam bidang ini. Bahasa memiliki fungsi yang lebih dinamis. Dahulu bahasa adalah representasi realitas, semenjak saat itu ternyata bahasa dapat difungsikan sebagai pembentuk realitas.
Kita percaya bahwa masyarakat Jawa itu dapat dikategorikan dengan kelompok priyayi, abangan, dan santri. Kita juga percaya bahwa ada istilah islam tradisional dan islam moderat dan islam Nusantara. Kita juga percaya bahwa orang surau tarekat adalah Islam tradisional, tradisional tentu artinya tidak modern, tidak maju, tidak keren.
Akhirnya kita lebih tahu bahwa Ibrahim Dt. Tan Malaka sebagai alumni Rijks Kweekschool Haarlem bukan sebagai alumni surau tarekat. Bahasa yang membawa kategori-kategori yang dipopulerkan oleh orang yang berpengaruh seperti Datuak Ibrahim kemudian membentuk realitas baru, dan realitas itu dipercaya sebagai yang benar adanya. Ketika kita percaya dan patuh pada kategori, skemata dan metafora yang dibuat menggunakan leksikon itu, maka pada saat itu kita tertawan oleh leksikon.
Ada hal yang perlu kita pahami dengan ilmu kognisi ini (cognitive psychology, cognitive science, cognitive linguistics). Ada tiga konsep penting, yaitu image, perception, dan behavior. Image itu adalah konstruksi; dia adalah hasil bentukan. Image ini kemudian membentuk persepsi. Persepsi ini bisa bersifat perseorangan, bisa juga bersifat sosial.
Namun berdasarkan hukum sosial, persepsi sosial dianggap sebagai kebenaran konvensional dan dianggap lebih benar. Setelah image itu membentuk persepsi, kemudian persepsi itu yang merubah atau membentuk behavior, atau prilaku. Penawanan gaya baru yang menggunakan bahasa itu adalah dengan mengontrol image. Setelah image berhasil ditentukan dan dikontrol maka persepsi dan perilaku juga dapat dikontrol. Jangan lupa image itu adalah leksikon.
Penulis: Nofel Nofiadri (Dosen UIN Imam Bonjol Padang)