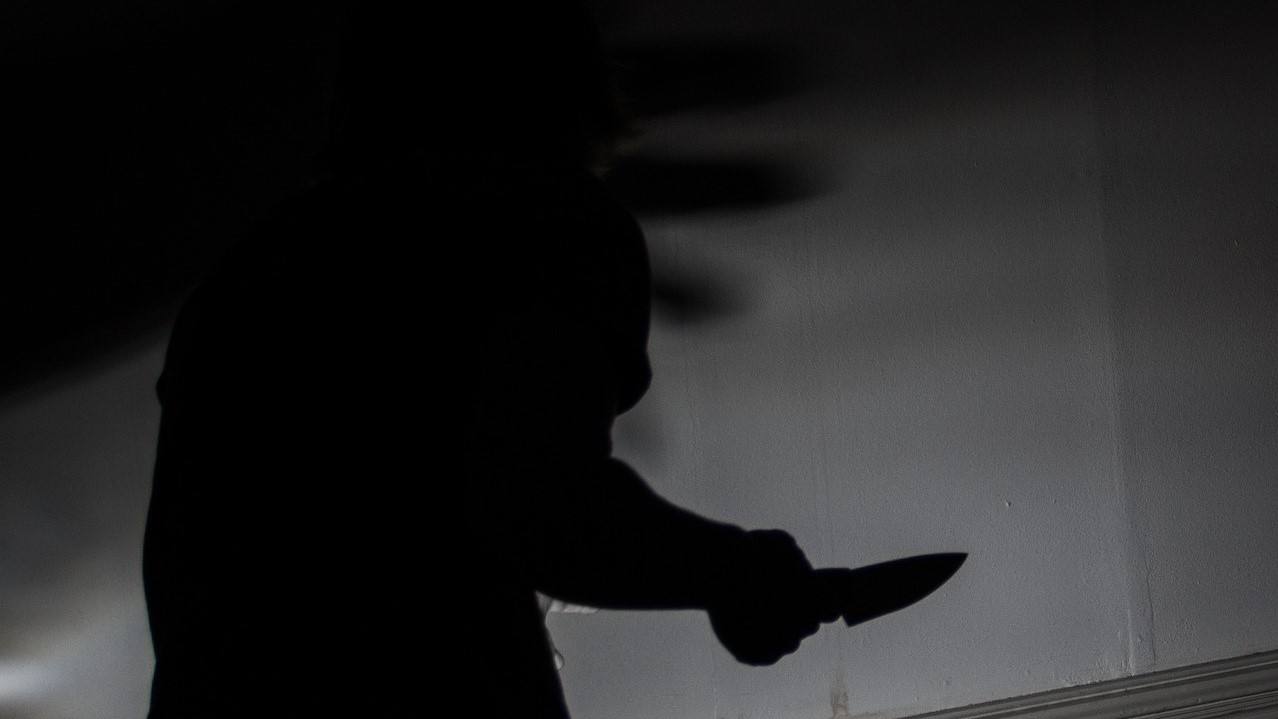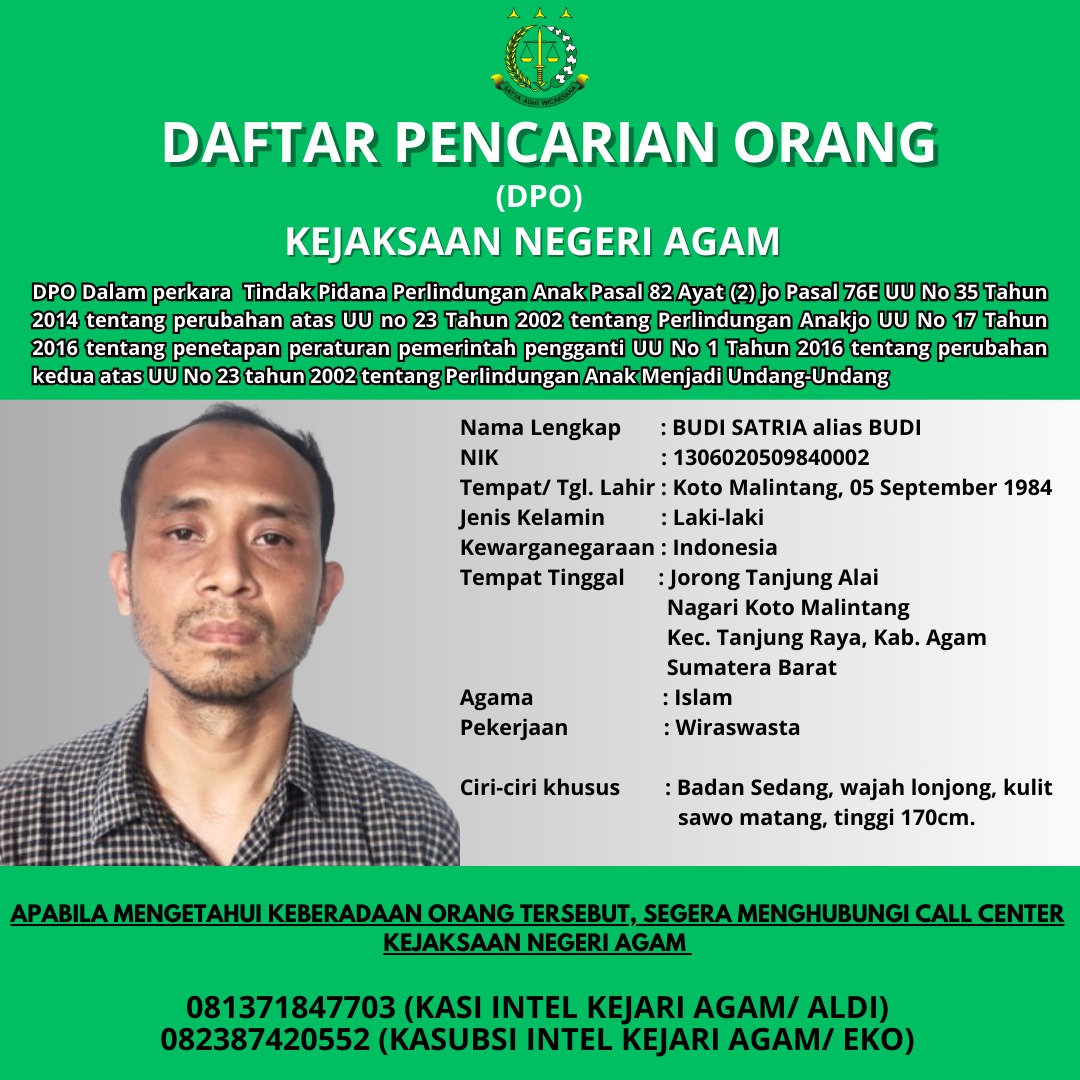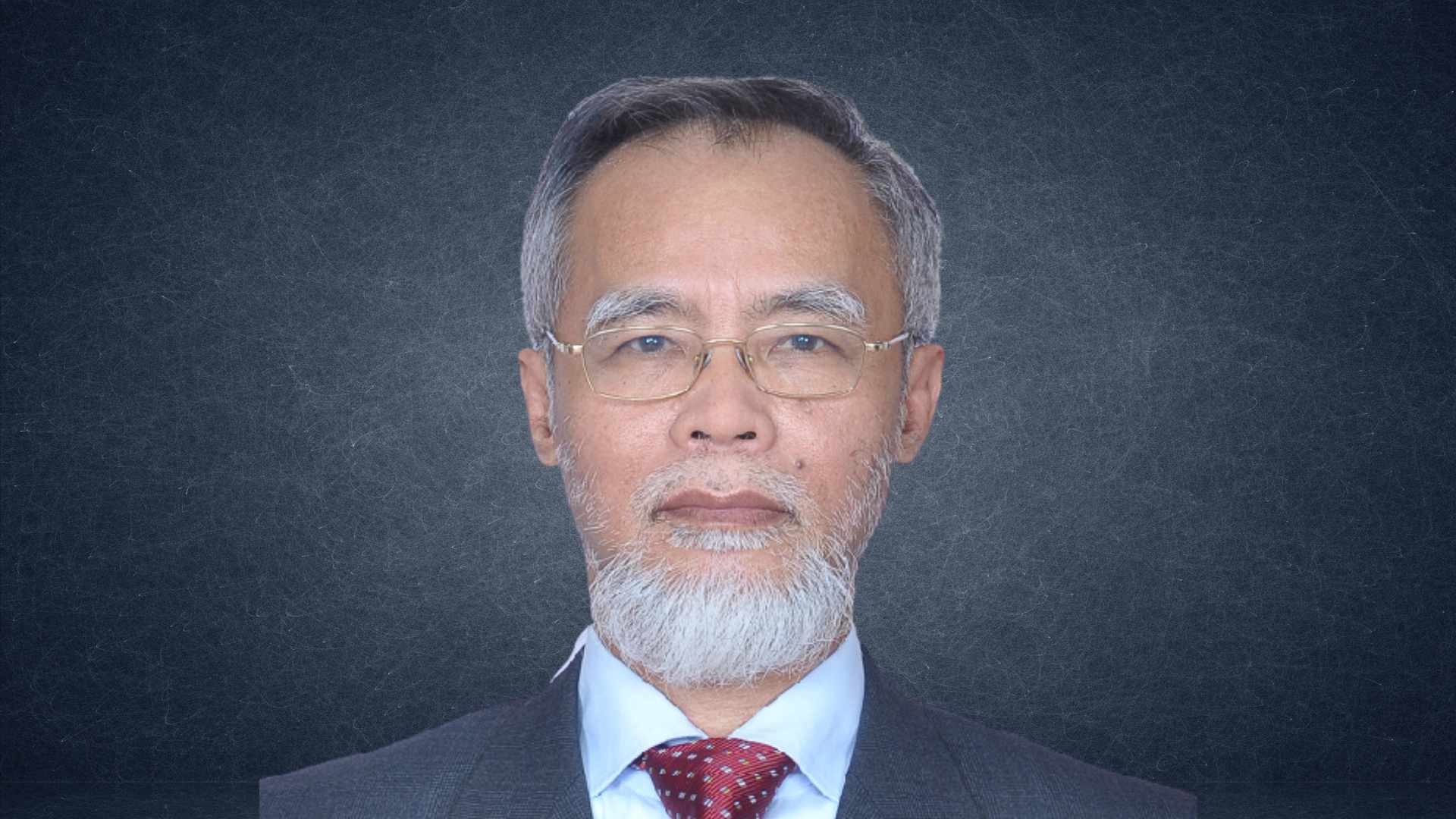Pemerintah telah merilis proyeksi asumsi makroekonomi untuk tahun 2026 dengan rentang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% hingga 5,8%. Di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian, target ini tampak ambisius. Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) justru lebih konservatif di angka 4,7% untuk Indonesia. Perbedaan ini menunjukkan adanya ekspektasi optimisme fiskal yang kuat dari pemerintah. Akan tetapi, tanpa reformasi struktural seperti penguatan industri pengolahan, produktivitas tenaga kerja, dan perluasan investasi berkualitas, peluang untuk mendekati batas atas proyeksi tersebut akan sangat kecil.
Lebih jauh, pemerintah merancang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kisaran 2,48% hingga 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pertanyaannya, apakah ruang fiskal sebesar itu cukup untuk membiayai program prioritas seperti makan bergizi gratis dan modernisasi pertahanan? Dengan dominasi belanja wajib dan subsidi yang terus membesar, kapasitas belanja strategis menjadi terbatas. Kecuali pemerintah mampu meningkatkan rasio penerimaan pajak secara signifikan, program-program ambisius tersebut berpotensi terkendala pembiayaan yang berkelanjutan.
Dari sisi eksternal, asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS mencerminkan ekspektasi pelemahan terhadap posisi saat ini. Ini membawa konsekuensi terhadap daya beli masyarakat. Depresiasi rupiah akan mendorong kenaikan harga barang impor dan memperbesar tekanan inflasi. Apalagi, sebagian besar bahan baku industri nasional masih bergantung pada luar negeri. Pemerintah harus memperkuat ketahanan pangan dan energi domestik untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat kelas bawah tidak menjadi korban utama fluktuasi nilai tukar.
Inflasi sendiri diasumsikan tetap rendah, antara 1,5% hingga 3,5%. Di atas kertas, angka ini selaras dengan target Bank Indonesia. Namun realitasnya, potensi tekanan harga dari sisi suplai—seperti pangan dan energi—belum tereliminasi sepenuhnya. Ketika permintaan mulai meningkat karena program sosial dan konsumsi pulih, dan di saat yang sama terjadi gangguan logistik atau anomali iklim, maka inflasi bisa menembus batas atas target. Pemerintah perlu menyiapkan instrumen stabilisasi yang lebih antisipatif, bukan sekadar reaktif.
Stabilitas sistem keuangan juga perlu menjadi perhatian. Asumsi suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada di kisaran 6,6% hingga 7,2%. Angka ini bisa menjaga minat investor, tetapi juga berisiko meningkatkan biaya utang pemerintah. Kenaikan yield ini juga dapat merembes ke sektor perbankan, memperlambat ekspansi kredit produktif. Jika tidak diimbangi dengan efisiensi fiskal dan koordinasi yang solid antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sistem keuangan bisa tertekan oleh beban ganda: pembiayaan publik dan stagnasi kredit swasta.
Akhirnya, risiko terhadap pencapaian target ekonomi 2026 sangat nyata. Dari luar, ketegangan geopolitik, pelemahan mitra dagang utama, hingga fragmentasi rantai pasok bisa menghambat ekspor dan investasi. Dari dalam negeri, tantangan seperti lemahnya kapasitas birokrasi daerah, keterbatasan kualitas belanja, dan belum tuntasnya reformasi sektor tenaga kerja akan terus menjadi ganjalan. Pemerintah harus menyiapkan skenario cadangan dan kebijakan adaptif untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.
Menakar proyeksi makro bukan sekadar soal angka—ini soal kredibilitas. Publik perlu diyakinkan bahwa setiap target didasarkan pada fondasi kebijakan yang nyata, bukan optimisme sepihak. Dalam ekonomi, kepercayaan lahir bukan dari janji, tetapi dari kemampuan negara mengeksekusi dengan presisi dan konsistensi.
*Penulis: Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE. MA (Dosen Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)