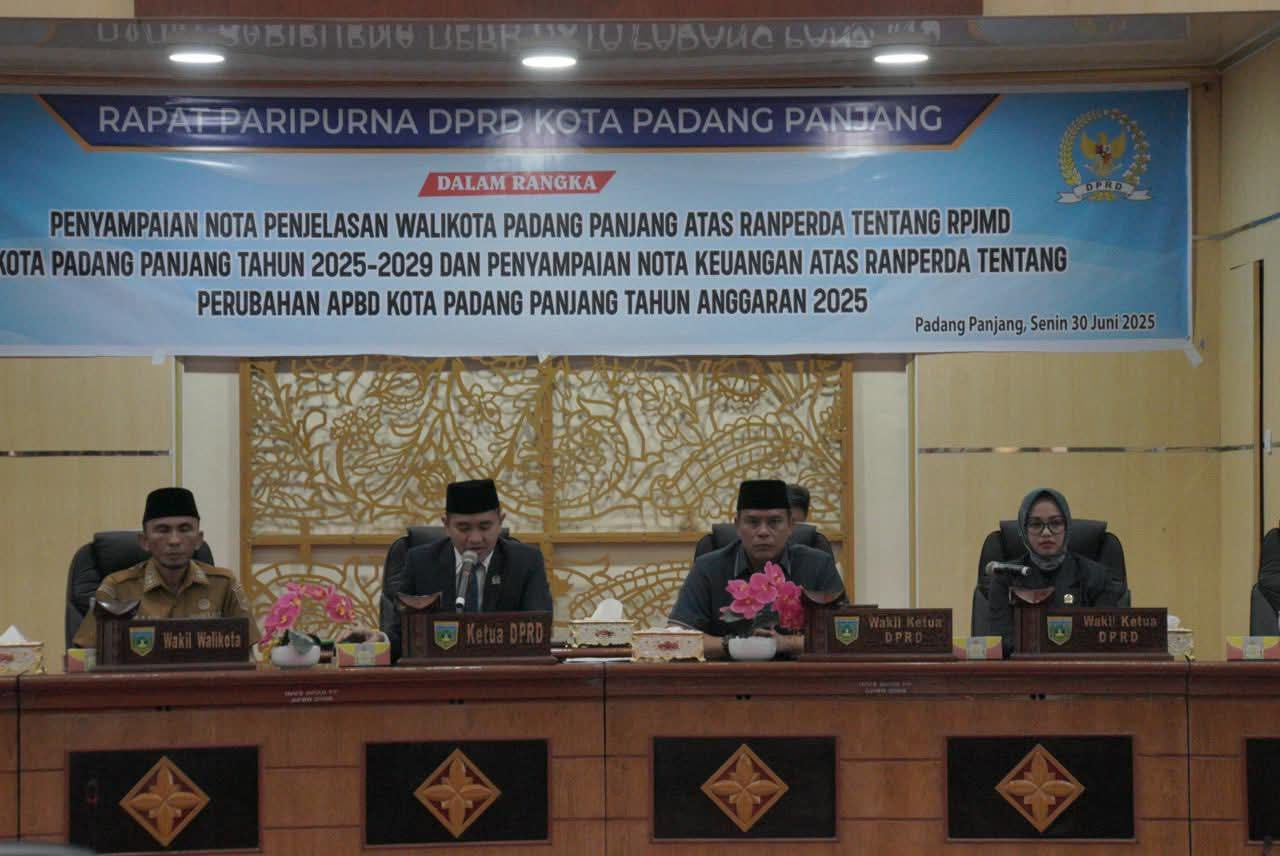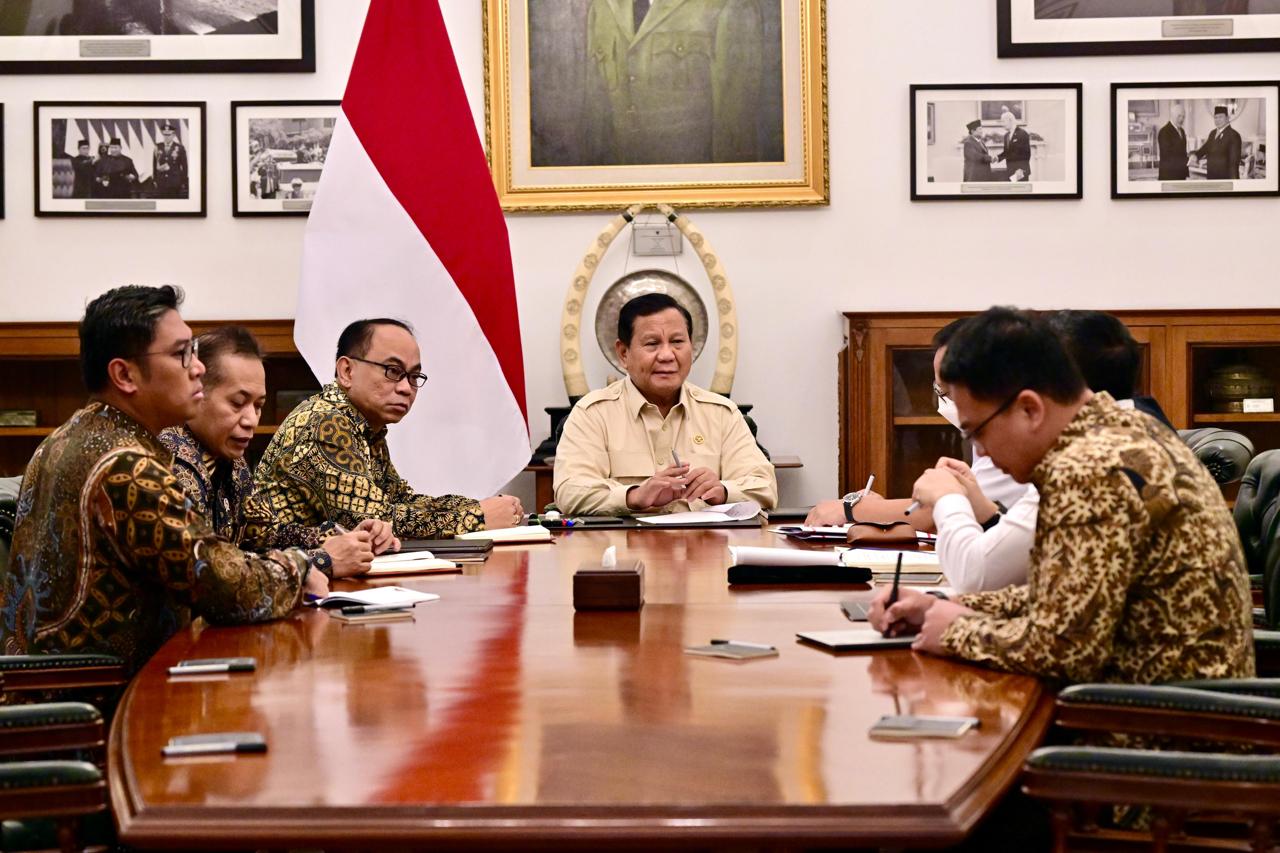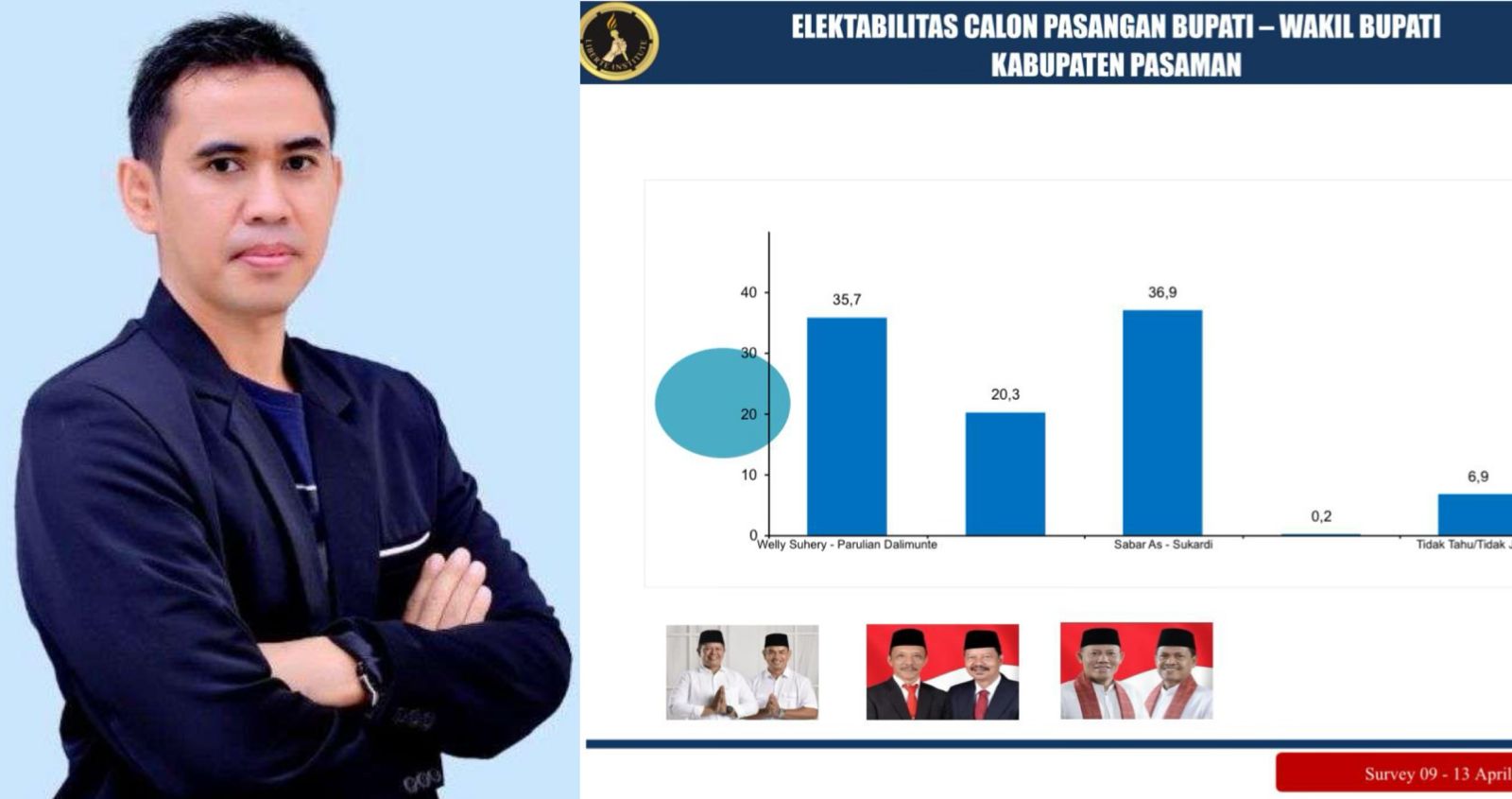Oleh: Habibur Rahman
Pada pertengahan Februari 2025 lalu kita dapat melihat ribuan pelajar di sejumlah daerah di Papua, terutama Papua Pegunungan turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan oleh pemerintah pusat.
Aksi ini bukanlah sekadar protes spontan, melainkan bentuk artikulasi kritik yang menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan nasional yang dianggap gagal membaca kebutuhan nyata masyarakat lokal, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan yang layak dan merata.
Gelombang penolakan terhadap MBG pertama kali mencuat dari Kabupaten Yahukimo, yang kemudian menyulut resonansi gerakan serupa di wilayah lain seperti Intan Jaya, Jayawijaya, Jayapura, hingga Nabire. Gerakan ini mengindikasikan bahwa suara-suara dari daerah yang selama ini terpinggirkan mulai menemukan jalannya dalam pusaran wacana nasional.
Di tengah euforia politik yang mengagung-agungkan keseragaman program, para pelajar Papua justru menghadirkan narasi tandingan: bahwa pendidikan adalah fondasi utama menuju kesejahteraan, bukan bantuan instan berupa makan siang gratis yang sifatnya jangka pendek dan konsumtif.
Penolakan terhadap MBG bukan berarti menolak kebutuhan akan gizi yang layak, melainkan menyuarakan bahwa prioritas pembangunan Papua seharusnya difokuskan pada pembenahan sektor pendidikan secara struktural dan berkelanjutan. Akar masalah di Papua, terutama jika kita berbicara Papua Pegunungan, bukanlah kekurangan asupan makan siang, melainkan keterbatasan akses terhadap sekolah, minimnya sarana belajar, absennya guru, dan kurikulum yang tidak kontekstual dengan realitas sosial-budaya setempat.
Dalam lanskap agraris dan semi-subsisten Papua Pegunungan, masyarakat masih mengandalkan sumber pangan lokal seperti keladi, pisang, buah merah, buah woromo, dan ubi jalar itu semua adalah sejenis umbi-umbian yang telah menjadi komoditas berharga sebagai bahan makanan pokok.
Ironisnya, program MBG yang dijalankan pemerintah justru mengusung menu yang asing bagi kultur makan masyarakat lokal, tanpa mempertimbangkan aspek kearifan pangan daerah. Ketidaksesuaian ini mempertegas adanya jarak epistemik antara pembuat kebijakan dan masyarakat yang menjadi subjek kebijakan.
Kekayaan alam Papua yang melimpah sesungguhnya telah menyediakan sumber daya pangan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan masyarakat tanpa ketergantungan berlebihan pada program-program dari pusat, hanya berbeda hal jika kita hendak membahas kesejahteraan di bumi Cendrawasih ini, mereka tidur di atas emas tapi sama susah untuk menikmati kekayaan alam itu.
Jikalau kita berbicara soal sistem pertanian tradisional dan budaya berburu masih menjadi praktik yang hidup di banyak komunitas. Maka dari itu, intervensi negara dalam bentuk makan siang gratis seringkali tampak artifisial dan tidak menjawab urgensi utama: bagaimana menghapus ketimpangan akses pendidikan dan memberdayakan sumber daya manusia Papua dari akar rumput.
Sebagaimana yang dihadirkan oleh (CELIOS) sebuah lembaga riset independen di Indonesia yang fokus pada kajian ekonomi dan hukum, khususnya terkait kebijakan publik, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan, dijelaskan bahwa penerapan program MBG di negara-negara seperti India, Brasil, dan Meksiko memang menunjukkan potensi positif dalam menanggulangi masalah gizi.
Akan tetapi, pendekatan 'one-size-fits-all' seperti yang kini diupayakan di Indonesia berisiko mengabaikan kompleksitas sosial dan geografis, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keunikan karakteristik seperti Papua. CELIOS bahkan merekomendasikan penerapan model berbasis wilayah dengan pendekatan geografis untuk desa dan pendekatan individu untuk kota sebagai alternatif yang lebih efektif dan kontekstual.
Realitas Papua Pegunungan jauh lebih kompleks dari sekadar indikator kemiskinan atau kekurangan gizi. Daerah ini dikelilingi oleh tantangan geografis yang ekstrem, infrastruktur yang minim, dan kondisi sosial-politik yang tidak stabil. Konflik bersenjata, pengungsian, dan keterbatasan layanan publik telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.
Jika kita tarik kembali kepada peristiwa demonstrasi pertengahan Februari lalu, tampaknya tindakan represif masih berlangsung di daerah tersebut, tidak hanya kepolisian bahkan ASN melakukan hal tersebut, sebagaimana yang dijelaskan pada artikel yang dikeluarkan oleh Amnesty Indonesia, Usman Hamid, menjelaskan:
“Mencegat apalagi menangkap siswa yang hendak melakukan aksi damai menolak program MBG tanpa alasan hukum yang dibenarkan adalah bentuk pelanggaran HAM yang sangat nyata yang dipertontonkan oleh kepolisian di Tanah Papua. Penggunaan tembakan peringatan serta gas air mata dalam merespons aksi pelajar yang sedang berdemonstrasi jelas berlebihan.
Oleh karena itu polisi harus mengusut apakah tindakan oleh anggotanya tersebut dilakukan sudah sesuai aturan. Mengeluarkan tembakan peringatan dan menembakkan gas air mata secara serampangan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM oleh aparat", ujarnya.
Bahkan, seorang ASN Disdik di Nabire viral di sebuah video media sosial, mendaratkan kakinya di punggung salah satu demonstran di depan polisi, dan polisi hanya melihatnya tanpa melarangnya.
Kembali kepada konteks ulasan kita, hal yang wajar ketika ribuan pelajar di Tanah Papua itu menuntut untuk diprioritaskan pada bidang pendidikan, kenapa demikian? Kita bisa lihat data Kemendikdasmen yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Nduga saja contohnya, hanya terdapat 43 SD, 9 SMP, dan 2 SMA, angka yang sangat tidak proporsional dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Bergeser kepada data makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, turut mengafirmasi keterbelakangan ini, bahwasanya rata-rata lama sekolah masyarakat di Papua Pegunungan tercatat berada pada angka 5,10 tahun, dengan harapan lama sekolah 9,97 tahun, angka terendah di seluruh Indonesia. Data ini bukan sekadar statistik; ia adalah potret sistemik dari ketidakadilan dalam distribusi pembangunan pendidikan, jadi masih mau bilang ribuan pelajar Papua yang demo itu ditunggangi?
Maka, jika negara benar-benar ingin menjawab persoalan Papua secara substantif, maka arah kebijakan harus difokuskan pada upaya pemenuhan hak pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan sekolah di distrik-distrik terpencil harus menjadi prioritas, dengan diiringi perekrutan guru lokal yang memahami nilai dan budaya komunitas setempat. Kurikulum harus disesuaikan dengan bahasa, cara berpikir, dan nilai-nilai lokal agar pembelajaran menjadi kontekstual dan bermakna.
Subsidi pendidikan juga harus bersifat menyeluruh dan merata, tidak hanya menutupi biaya SPP, tetapi juga kebutuhan non-akademis seperti seragam, alat tulis, transportasi, dan akses internet. Ini merupakan langkah konkret untuk mengurangi angka putus sekolah yang tinggi di daerah tersebut. Pemerintah juga perlu memperluas program afirmatif seperti beasiswa yang terarah, agar menjangkau lebih banyak pelajar Papua yang berpotensi. Pendampingan intensif dan keberlanjutan dalam program beasiswa harus dijamin agar tidak hanya sekadar memberikan akses, tetapi juga memastikan keberhasilan studi dan kontribusi nyata bagi daerah asal.
Di samping itu, peningkatan kapasitas guru lokal melalui pelatihan yang berkelanjutan harus menjadi strategi jangka panjang. Guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang mampu membangun kepercayaan dan harapan di tengah komunitas.
Selanjutnya, program MBG memang masih dapat dijalankan, tetapi dengan pendekatan yang lebih selektif dan adaptif. Sasaran utama seharusnya adalah anak-anak yang benar-benar mengalami kondisi kekurangan gizi akut, bukan diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah. Dengan alokasi anggaran MBG yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun, akan jauh lebih strategis jika sebagian besar dari dana tersebut dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, serta menjamin keterjangkauan dan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak Papua.
Pendidikan adalah jalan menuju perubahan struktural yang berkelanjutan. Ia bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membuka pintu menuju kebebasan, pemberdayaan, dan keadilan, dan pada akhirnya kita diberitahu oleh para pelajar tersebut, bahwa sebuah daerah yg selama ini digambarkan jauh dari kemajuan yakni tanah Papua, justru malah menampilkan kemajuan itu sendiri. Generasi cerdas yg mementingkan pendidikan daripada urusan perut, dalam aksinya mereka menolak program makan bergizi gratis, dan memilih untuk mendapatkan prioritas dalam pendidikan, tapi sayang aksi demonstrasi mereka dinilai ditunggangi elit.
*Penulis: Habibur Rahman, Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Aktif menulis tentang sejarah ulama-ulama tarekat di Sumatra Barat serta dinamika dan problematika Surau Tradisional Minangkabau.