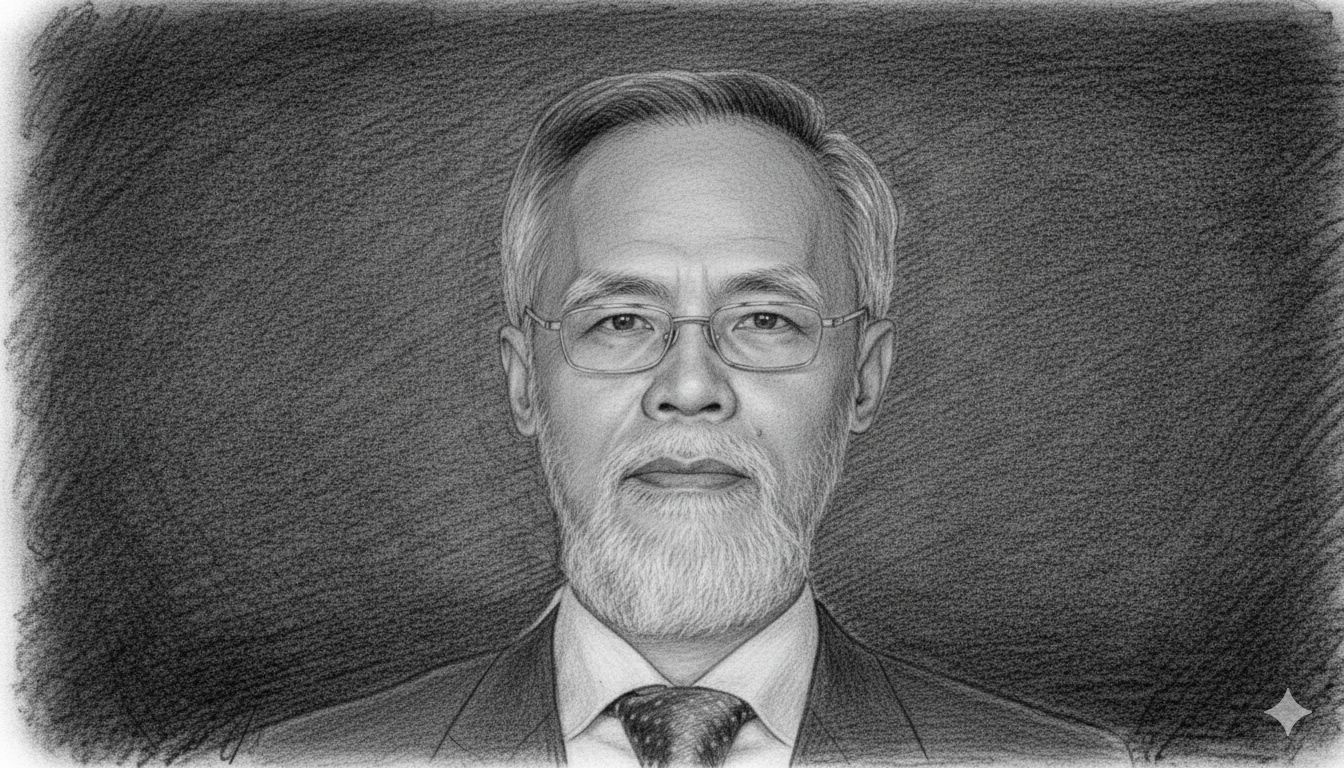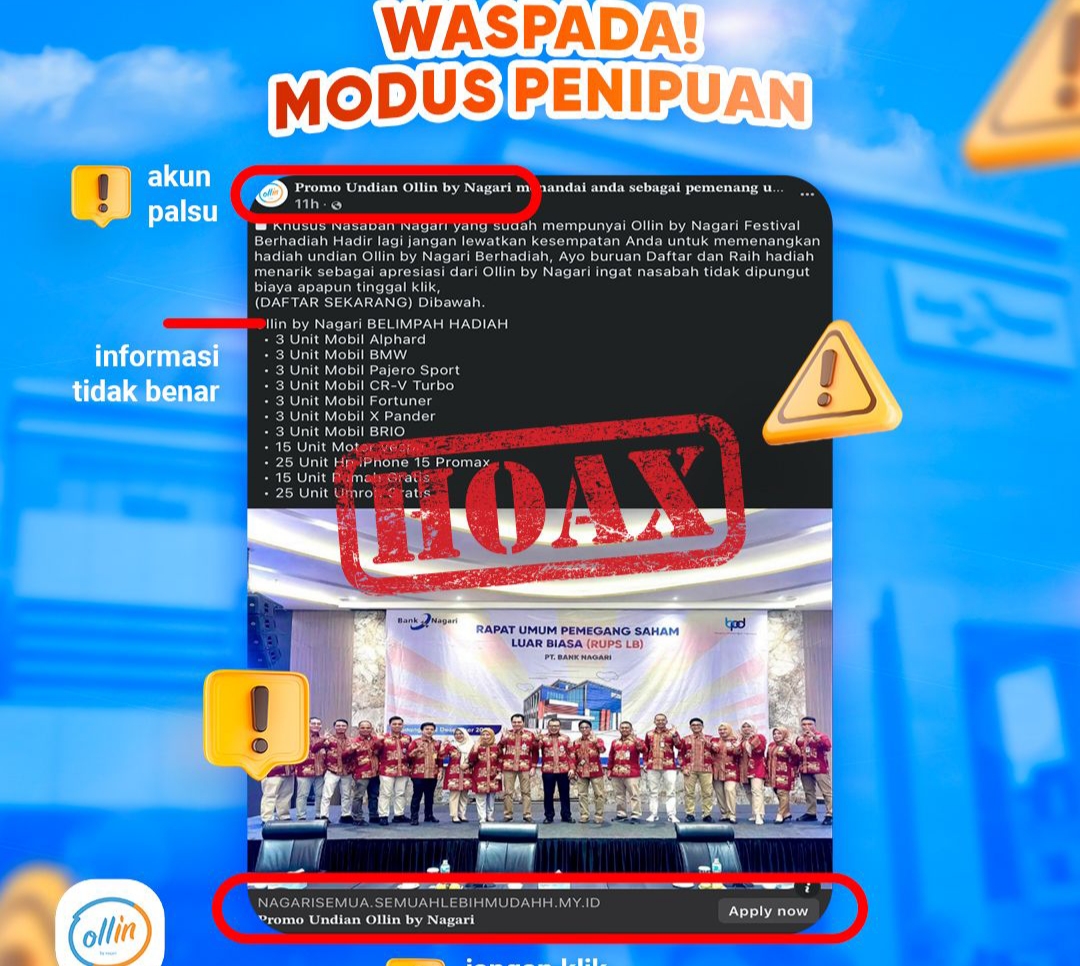Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengolahan Sampah menjadi Energi (PSE) termasuk menjadi energi Listrik (PSEL) lahir dengan semangat memecahkan persoalan sampah kota besar melalui pendekatan teknologi tinggi. Namun, semangat tersebut justru melahirkan serangkaian konsekuensi kebijakan yang berpotensi mempersempit ruang inovasi pengelolaan sampah secara multipurpose. Dalam regulasi ini, pengolahan sampah secara eksplisit diarahkan untuk menghasilkan energi listrik dan energi lainnya sementara bentuk pengolahan lain—seperti pengomposan, pemilahan 3R, produksi bahan baku industri sekunder—nyaris tidak mendapat ruang legal. Akibatnya, orientasi tunggal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah berusaha memecahkan masalah lingkungan melalui pendekatan industrialisasi energi, bukan melalui tata kelola sampah yang holistik.
Ketika peraturan publik mengunci satu bentuk teknologi dan produk akhir, maka kebijakan tersebut kehilangan fleksibilitas adaptif terhadap variasi kondisi daerah. Setiap kota memiliki karakter sampah, kapasitas fiskal, dan infrastruktur yang berbeda. Menyeragamkan arah pengolahan sampah ke bentuk energi berarti mengabaikan keberagaman ekologi dan ekonomi lokal. Di sinilah muncul kontradiksi mendasar: Perpres ini seolah mendefinisikan “pengolahan sampah” bukan sebagai proses pengelolaan sumber daya sisa secara berkelanjutan, melainkan sebagai “produksi energi” yang menuntut logika bahan baku dan jaminan pasokan tetap—suatu pendekatan yang bertentangan dengan hakikat dinamis sampah sebagai residu aktivitas manusia yang seharusnya semakin berkurang.
Menjamin Jumlah Pasokan Sampah Menjadi Sebuah Ironi dalam Ekonomi Sirkular
Salah satu ketentuan yang paling problematik dari Perpres 109/2025 adalah keharusan menjamin pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari bagi setiap fasilitas PSEL. Ketentuan ini secara implisit menempatkan sampah sebagai komoditas bahan baku industri, bukan sebagai beban ekologis yang harus ditekan melalui upaya pengurangan di hulu. Dalam sistem ekonomi sirkular, prinsip utama yang dipegang adalah reduce, reuse, recycle—mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, menggunakan kembali produk yang masih layak, dan mendaur ulang material yang bernilai. Dengan demikian, semakin baik kinerja pengelolaan sampah di hulu, seharusnya semakin sedikit volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir. Namun Perpres ini justru membalik logika tersebut: agar pabrik PSEL dapat beroperasi, volume sampah harus dijaga tetap tinggi.
Paradoks ini menimbulkan dilema kebijakan. Di satu sisi, pemerintah daerah didorong untuk menjalankan kebijakan pengurangan sampah di sumber sesuai mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di sisi lain, mereka juga diwajibkan memastikan kuantitas sampah tertentu untuk memberi makan tungku PSEL. Bila pasokan sampah menurun karena kebijakan daur ulang berjalan efektif, maka operasi PSEL bisa terancam tidak efisien. Akibatnya, pemerintah daerah mungkin akan menahan atau bahkan meniadakan inisiatif pengurangan di hulu demi menjaga pasokan “bahan baku” PSEL. Ironi inilah yang menjadikan Perpres 109/2025 secara konseptual bertentangan dengan semangat transisi menuju ekonomi sirkular.
Sampah Bukan Seperti Bahan Baku Industri
Sampah pada hakikatnya berbeda dari bahan baku industri. Bahan baku industri memiliki sifat homogen, dapat dikendalikan kualitas dan kuantitasnya, serta memiliki nilai tambah yang terukur. Sebaliknya, sampah bersifat heterogen, fluktuatif, dan tidak memiliki nilai ekonomi positif kecuali melalui intervensi pengelolaan yang memerlukan biaya besar. Menetapkan PSEL sebagai proyek berbasis investasi berarti menempatkan sampah pada logika industri—yang membutuhkan kepastian pasokan, kualitas, dan keuntungan finansial. Namun dalam kenyataannya, tidak ada mekanisme ekonomi yang mampu menjamin kontinuitas pasokan sampah tanpa mengorbankan tujuan pengurangan timbulan.
Secara praktis, menjamin pasokan 1.000 ton sampah per hari berarti pemerintah harus mengubah pola pengelolaan kota. Sistem pengumpulan, transportasi, dan pembuangan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pabrik, bukan kebutuhan ekologis masyarakat. Dalam hal ini, Perpres 109/2025 cenderung memindahkan beban lingkungan ke bentuk baru: dari tumpukan sampah ke tumpukan biaya logistik dan energi. Pemerintah daerah akan menghadapi dilema anggaran antara membiayai pengurangan sampah di hulu atau memastikan suplai sampah untuk PSEL di hilir. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pilihan yang rasional secara politik bisa saja justru yang paling tidak rasional secara lingkungan.
Penetapan Harga Jual Listrik Produk PSEL ke PLN menjadi Beban Fiskal Terselubung
Perpres 109/2025 juga mengatur kewajiban PLN untuk membeli listrik hasil PSEL dengan harga tetap sebesar USD 0,20 per kWh. Ketentuan harga ini, yang ditetapkan melalui Perpres, menimbulkan tanda tanya besar dalam tata kelola energi nasional. Dalam sistem energi yang sehat, harga jual listrik semestinya mencerminkan efisiensi teknologi dan kondisi pasar. Namun penetapan harga tetap melalui regulasi presiden berarti pemerintah mengambil risiko fiskal untuk menutupi ketidakefisienan sistem. Bila biaya produksi listrik dari PSEL jauh di atas harga jual ke konsumen, maka selisihnya berpotensi menjadi beban kompensasi pemerintah atau PLN—yang ujungnya tetap bersumber dari anggaran publik.
Kebijakan harga tetap ini juga menutup ruang inovasi teknologi dan kompetisi pasar. Alih-alih mendorong riset dan pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih efisien, Perpres justru memberikan jaminan keuntungan bagi investor dengan risiko minimal. Hal ini berpotensi menciptakan distorsi pasar di sektor energi terbarukan. Sementara proyek energi surya, biomassa, atau mikrohidro berjuang menekan biaya agar kompetitif, PSEL mendapatkan harga premium tanpa mempertimbangkan biaya lingkungan yang ditimbulkannya. Pada akhirnya, kebijakan semacam ini lebih mencerminkan semangat penyelamatan proyek daripada penyelamatan lingkungan.
APBD Sebagai Penopang Rantai Pasok Sampah
Aspek lain yang tidak kalah problematik adalah ketentuan bahwa biaya pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke fasilitas PSEL menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD. Artinya, meskipun proyek PSEL diklaim sebagai proyek investasi, sebagian besar biaya operasional logistik tetap ditanggung publik. Dalam perspektif ekonomi publik, hal ini menciptakan hidden subsidy—subsidi terselubung yang mengalir dari anggaran daerah ke proyek swasta. Akibatnya, manfaat fiskal yang dijanjikan dari proyek investasi tersebut menjadi ilusi. Pemerintah daerah akan menghadapi beban ganda: menanggung biaya pengumpulan dan transportasi, serta memastikan kontinuitas pasokan yang bisa menguras kemampuan fiskal mereka.
Kondisi ini sangat kontras dengan prinsip polluter pays atau tanggung jawab produsen dan konsumen atas limbah yang mereka hasilkan. Alih-alih menempatkan tanggung jawab pada produsen barang atau sektor industri, Perpres ini justru membebankan tanggung jawab pengangkutan ke pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, struktur kebijakan seperti ini dapat mengurangi kemampuan daerah membiayai program pengurangan sampah berbasis masyarakat, bank sampah, dan sistem daur ulang lokal yang jauh lebih murah dan berdaya guna sosial. Dengan kata lain, APBD dipaksa menopang sistem yang secara struktural tidak efisien dan tidak berkelanjutan.
Ketimpangan Logika Penjaminan Jumlah Pasokan Sampah yang Harus Dipasok oleh Daerah ke Lokasi PSEL
Dari sisi desain investasi, Perpres 109/2025 tampak mengasumsikan bahwa sektor swasta akan tertarik membangun fasilitas PSEL sepanjang ada jaminan pasokan sampah dan pembelian listrik oleh PLN. Namun asumsi ini mengabaikan realitas keterbatasan fiskal daerah dan kapasitas kelembagaan mereka. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan membangun sistem pengumpulan dan logistik yang mampu memastikan suplai sampah 1.000 ton per hari secara konsisten. Dalam praktiknya, skema investasi seperti ini akan bergantung pada dukungan fiskal pemerintah pusat atau pinjaman luar negeri. Akibatnya, proyek yang dirancang untuk efisiensi justru berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang.
Selain itu, proyek besar seperti PSEL berpotensi memperlebar ketimpangan antar-daerah. Hanya kota-kota besar dengan volume sampah tinggi yang bisa memenuhi syarat pasokan minimal, sementara kota menengah dan kecil tidak akan tersentuh oleh program ini. Dengan demikian, orientasi kebijakan energi dari sampah justru menciptakan eksklusi wilayah: hanya daerah dengan “masalah besar” yang mendapat “solusi mahal”. Padahal, dari perspektif pembangunan berkelanjutan, daerah dengan volume sampah lebih kecil justru lebih membutuhkan dukungan untuk memperkuat sistem pengelolaan berbasis komunitas dan inovasi lokal.
Paradigma Pengelolaan Sampah yang Adaptif
Untuk keluar dari jebakan logika tunggal PSEL, kebijakan nasional perlu meninjau kembali definisi pengolahan sampah dalam konteks multipurpose. Sampah dapat menjadi sumber energi, bahan baku daur ulang, atau sumber bahan organik untuk pertanian, tergantung pada karakter dan volume lokal. Prinsip kebijakan yang adaptif seharusnya memberi ruang bagi daerah untuk memilih kombinasi teknologi dan model bisnis yang paling sesuai dengan kapasitas fiskalnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip subsidiarity dalam tata kelola lingkungan: keputusan terbaik diambil sedekat mungkin dengan sumber masalahnya. Dengan cara ini, pengelolaan sampah tidak lagi menjadi proyek investasi semata, melainkan strategi pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, pembenahan kelembagaan juga penting untuk memastikan integrasi antara kebijakan energi dan kebijakan lingkungan. Selama ini, kedua sektor tersebut sering berjalan terpisah: energi melihat sampah sebagai bahan bakar, sedangkan lingkungan melihatnya sebagai beban yang harus dikurangi. Diperlukan kerangka kebijakan yang mampu menjembatani dua logika ini, misalnya melalui insentif fiskal untuk pengurangan sampah di hulu dan dukungan riset bagi teknologi pengolahan multifungsi. Dengan demikian, kebijakan energi dari sampah tidak lagi bersifat top-down dan seragam, tetapi adaptif, berkeadilan fiskal, dan berorientasi ekologis.
Menimbang Ulang Rasionalitas Perpres 109/2025 tentang Pengolahan Sampah Hanya Jalur Energi
Perpres Nomor 109 Tahun 2025 menghadirkan niat baik dalam mengatasi krisis sampah nasional, tetapi niat baik tersebut terperangkap dalam desain kebijakan yang lebih mencerminkan logika industri energi daripada logika pengelolaan sampah yang terakumlasi dan menumpuk terus. Dengan mengunci orientasi ke energi terutama ke energi listrik, menjamin pasokan minimal sampah, menetapkan harga listrik secara politis, dan membebankan biaya logistik ke APBD, kebijakan ini berpotensi menjadi solusi semu yang mengabaikan akar persoalan. Dalam jangka panjang, keberlanjutan fiskal daerah dan efektivitas kebijakan pengurangan sampah bisa terancam oleh struktur regulasi yang terlalu kaku ini.
Revisi terhadap Perpres ini sebaiknya mengembalikan semangat pengelolaan sampah ke akar prinsipnya: pengurangan, pemanfaatan ulang, dan daur ulang. Teknologi energi dari sampah bisa menjadi salah satu instrumen, tetapi bukan satu-satunya jalan. Ketika pemerintah mampu merumuskan kebijakan yang melihat sampah bukan sebagai komoditas industri, melainkan sebagai indikator efisiensi sosial, maka pengelolaan sampah akan lebih selaras dengan tujuan keberlanjutan nasional.
*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)