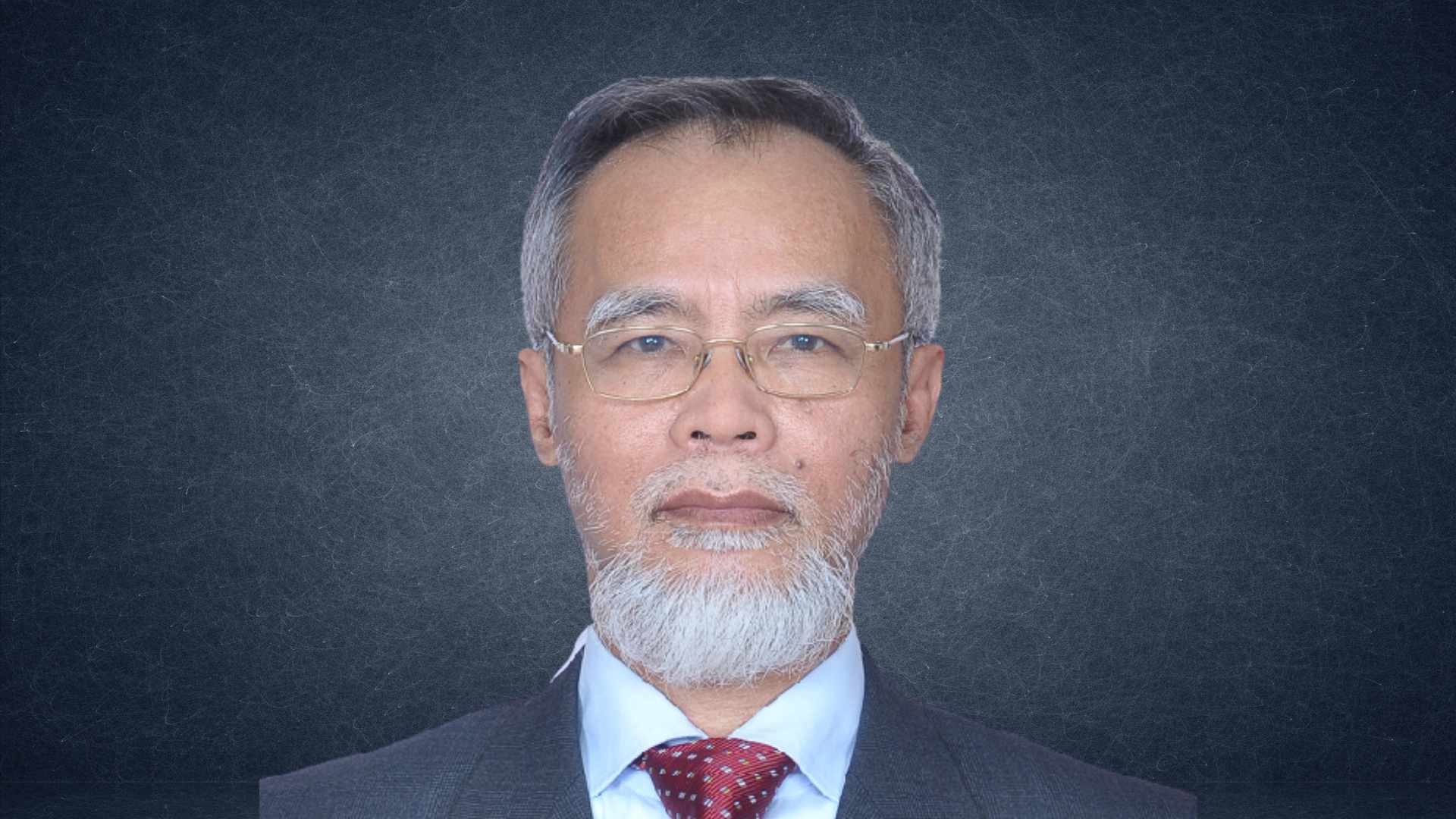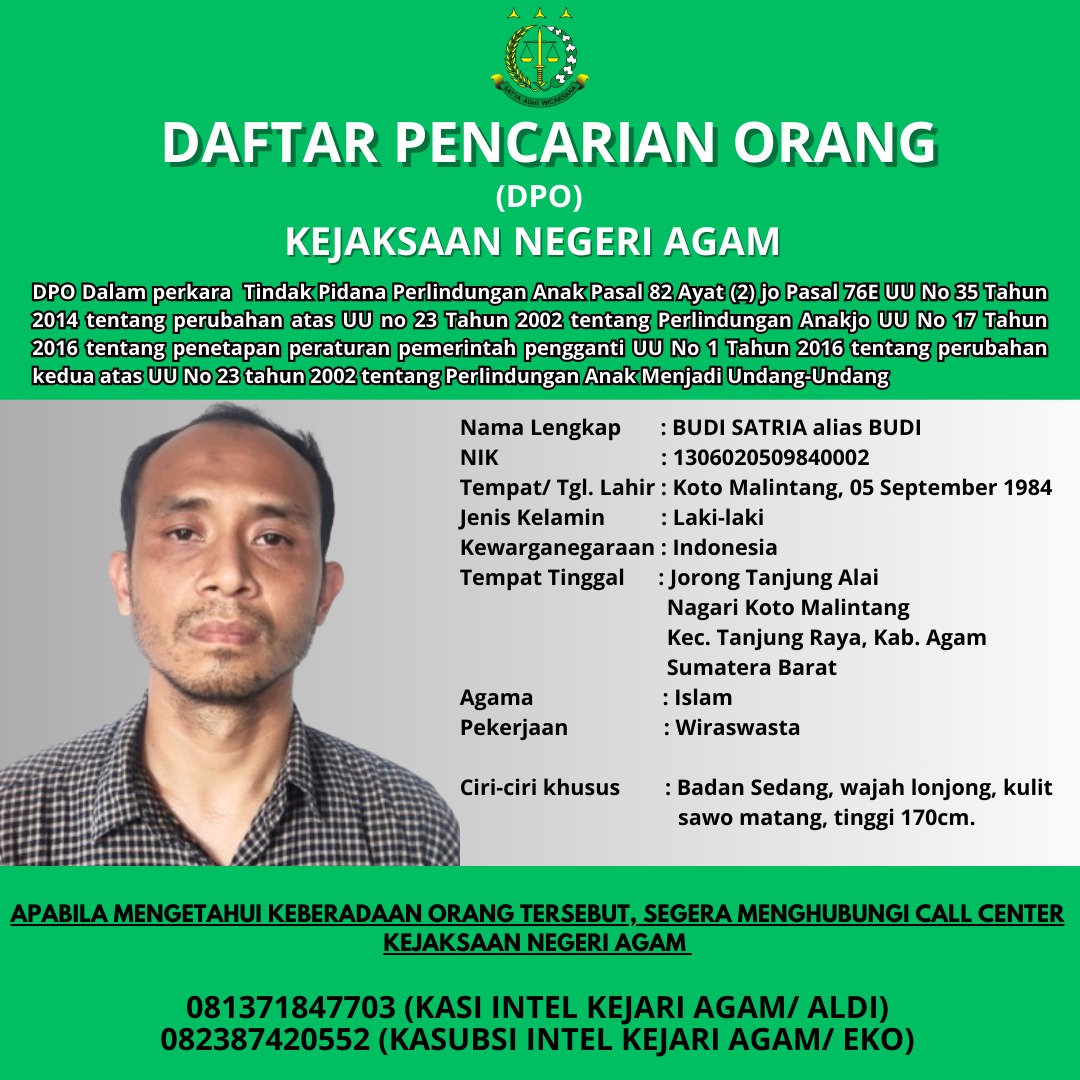Kampus adalah rumah kedua bagi kaum intelektual. Tapi, bila rumahnya sunyi dari karya ilmiah, masihkah layak disebut rumah ilmu? Di tengah gegap gempita seminar, pelatihan konten kreatif, hingga lomba-lomba debat ala Gen Z, satu pertanyaan menggelitik muncul: ke mana larinya tradisi menulis ilmiah mahasiswa?
Di berbagai fakultas komunikasi di Sumbar, termasuk di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Imam Bonjol Padang, ironi ini terasa nyata. Prodi Komunikasi, yang sejatinya menjadi pusat pengolahan gagasan dan penyampai pesan berbasis data, malah perlahan berubah menjadi tempat parade aktivitas pragmatis. Mahasiswa lebih hafal nama-nama aplikasi editing dibanding jurnal-jurnal ilmiah. Skripsi? Sekadar tiket menuju toga. Ironi zaman modern: semakin canggih teknologinya, semakin malas menulisnya.
Data dari Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa hanya 27% mahasiswa Indonesia yang pernah mempublikasikan karya ilmiah selama kuliah. Angka ini lebih menyedihkan lagi jika ditelusuri di kampus-kampus keagamaan. Padahal, salah satu indikator utama mutu perguruan tinggi adalah produktivitas ilmiah sivitas akademik. Bahkan UNESCO pun menekankan pentingnya budaya literasi ilmiah sebagai pondasi transformasi sosial yang berkelanjutan (UNESCO, 2021).
Lantas, mengapa mahasiswa tampak 'malas menulis'? Jawabannya tidak tunggal. Tapi mari kita buka satu per satu. Pertama, ada semacam mentalitas pragmatis di kalangan mahasiswa. Menulis dianggap beban, bukan proses berpikir. Mereka lebih sibuk membangun citra visual ketimbang argumentasi logis. Konten TikTok tiga menit lebih menarik dibandingkan esai delapan halaman. Tentu saja, tidak semua konten visual itu dangkal, tapi kalau narasi akademik saja ditinggalkan, bagaimana mungkin kita bisa menjadi bangsa pemikir?
Kedua, minimnya keteladanan akademik. Dosen yang seharusnya menjadi role model dalam publikasi kadang lebih sibuk mengejar tunjangan fungsional daripada membimbing riset secara substantif. Ibarat pepatah Arab, faqidusy-syai’ laa yu’thi yang tidak punya, tak bisa memberi. Banyak dari mereka yang bangga memamerkan karya ilmiah, padahal saat diperiksa lebih dalam, tangan yang sebenarnya menulis adalah asisten dosen, atau bahkan mahasiswa baru lulus. Bukan hanya numpang nama, tapi benar-benar tidak paham isi.
Sejalan dengan itu, harus dipahami bahwa: "Tulisan adalah jejak paling jujur dari pikiran manusia." Pramoedya Ananta Toer
Dan lantas ini bukan kabar burung. Banyak cerita beredar kadang dibisikkan di lorong kampus, kadang muncul sebagai status WhatsApp yang ambigu tentang dosen yang minta dibantu menulis jurnal internasional terindeks Scopus, tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban sertifikasi dosen atau kenaikan pangkat. Begitu hasilnya diterbitkan, nama mahasiswa raib, nama dosen naik pangkat. Selamat datang di dunia akademik tropis: panas oleh tuntutan, lembab oleh manipulasi.
Ketiga, iklim akademik yang minim apresiasi terhadap karya ilmiah. Sebuah tulisan reflektif atau artikel jurnal lebih sering masuk laci dosen ketimbang panggung diskusi. Mahasiswa tak pernah diajak berdialog tentang gagasannya, hanya disuruh menulis lalu dikoreksi ala kadarnya. Maka tak heran, menulis menjadi seperti ritual tanpa makna. Tidak ada ruang berekspresi, apalagi berdebat gagasan. Padahal, ruang diskusi dan dialog adalah napas dari kebebasan akademik.
Fenomena ini bukan hanya cermin kemalasan, tapi juga bentuk kegagalan sistemik dalam membangun budaya akademik yang sehat. Ilmiah menjadi slogan, bukan sikap. Komunikasi ilmiah dikalahkan oleh komunikasi instan. Kita terlalu sibuk mengejar viral, lupa pada esensi berpikir kritis.
Padahal, menulis ilmiah bukan hanya soal gaya bahasa baku atau kutipan standar APA. Ia adalah latihan berpikir, proses memahami dunia secara lebih dalam. Dalam setiap tulisan yang jujur dan terstruktur, tersembunyi upaya manusia menjelaskan kenyataan dengan akal dan bukti. Menulis bukan sekadar mengisi halaman, tapi membangun gagasan. Dalam kata lain, menulis ilmiah adalah bentuk perlawanan terhadap dangkalnya berpikir.
Bayangkan jika kampus-kampus kita penuh dengan mahasiswa yang rajin menulis gagasan dan dosen yang benar-benar membimbing, bukan hanya menyodorkan template penelitian lalu menghilang. Bayangkan jika seminar ilmiah dihadiri karena memang isi dan diskusinya berbobot, bukan sekadar pelengkap kegiatan organisasi. Bayangkan jika publikasi ilmiah menjadi bagian dari gaya hidup intelektual, bukan sekadar syarat administratif.
Urgensinya? Jelas. Di tengah banjir informasi dan hoaks digital, kemampuan menulis dan berpikir kritis adalah benteng terakhir mahasiswa. Jika para sarjana tidak menulis, siapa yang akan melawan narasi-narasi menyesatkan? Jika para dosen hanya mencantumkan nama tanpa kontribusi nyata, bagaimana mungkin kita mencetak ilmuwan masa depan?
Tidak hanya itu, budaya menulis juga merupakan alat penting dalam menjaga integritas akademik. Dunia akademik seharusnya menjadi tempat lahirnya gagasan, bukan pabrik sertifikat. Saat karya ilmiah hanya menjadi formalitas, kita kehilangan esensi pendidikan tinggi. Kita menghasilkan lulusan yang hafal teori, tapi tak mampu menulis satu argumen utuh. Sarjana tanpa tinta itulah mereka.
Kita perlu membangun ekosistem ilmiah dari bawah. Dimulai dari kelas-kelas yang memberi ruang debat dan diskusi yang sehat. Dari dosen yang benar-benar menjadi pembimbing, bukan sekadar pemberi nilai. Dari lembaga yang menghargai karya tulis sebagai warisan intelektual, bukan tumpukan arsip.
Saran? Banyak. Tapi mari mulai dari yang sederhana: jadikan menulis sebagai kebiasaan. Bentuk komunitas literasi di setiap prodi. Dorong kolaborasi riset antara dosen dan mahasiswa yang sehat, adil, dan transparan. Beri insentif bukan hanya untuk dosen yang publikasinya banyak, tapi juga bagi mahasiswa yang berani berpikir dan menulis. Dan tentu saja, berhentilah menormalisasi plagiarisme dan karya tempelan.
Penting pula untuk memperbaiki sistem reward dan evaluasi kinerja dosen. Jangan hanya mengejar kuantitas publikasi, tetapi pastikan kualitas dan prosesnya benar. Libatkan mahasiswa dalam proses riset yang sebenarnya, beri mereka peran dan pengakuan yang layak. Jika perlu, reformasi kebijakan kampus untuk mengatur keterlibatan mahasiswa secara adil dalam proyek dosen.
Terakhir, bagi siapapun yang merasa sedang atau pernah berkuliah, cobalah jujur: sudahkah kita menulis sebagai bentuk berpikir, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban? Sudahkah kita mengisi gelar sarjana dengan karya, bukan hanya kenangan wisuda? Jika belum, mari mulai hari ini. Karena tinta seorang sarjana adalah bukti bahwa ia pernah berpikir, bukan hanya pernah kuliah.
Hidup Mahasiswa! Tapi lebih hidup lagi, Mahasiswa yang Menulis. Dan lebih bermartabat lagi, Dosen yang memiliki karya dari hasil sendiri.
*Penulis : M. Afif Wafri (Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam)